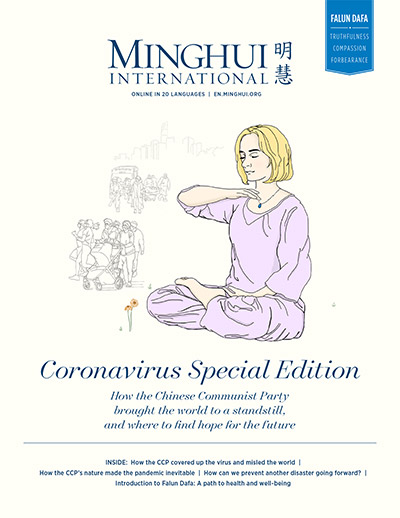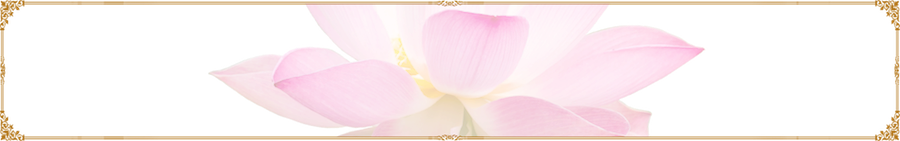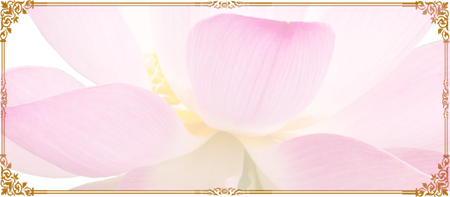(Minghui.org) Sepanjang sejarah, setiap sistem keyakinan yang lurus, baik di dalam maupun di luar Tiongkok, telah dianiaya. Penganiayaan itu sering menguji keyakinan para pengikut atas sistem keyakinan mereka. Terlepas dari legitimasi penganiayaan, tidak ada yang mampu menghancurkan sistem keyakinan yang lurus atau mencegah pengikut sejati mencapai kesempurnaan. Kesengsaraan itu malah mempertunjukkan tekad kuat para pengikut di tengah kegelapan, menginspirasi lebih banyak orang untuk bergabung dalam perjalanan mereka mengejar kebenaran dan menemukan tempat spiritualnya.
Berikut adalah beberapa contoh.
Penindasan terhadap agama Buddha
Agama Buddha dianiaya beberapa kali sepanjang sejarah Tiongkok. Yang pertama dimulai dengan Tuoba Tao, Kaisar Taiwu dari Wei Utara. Pada tahun 438, ia memerintahkan semua biksu di bawah usia 50 tahun untuk kembali ke kehidupan biasa. Mengikuti saran dari Cui Hao, seorang pejabat senior, kaisar membunuh biksu, menghancurkan patung Buddha, dan menghancurkan kuil pada tahun 446.
Setelah itu keduanya mendapatkan konsekuensinya. Kaisar dibunuh oleh para kasim, begitu pula kedua putranya. Dua tahun sebelum kematian kaisar, ia menjatuhkan hukuman ganda kepada Cui Hao, termasuk hukuman cambuk, penjara, pengasingan, dan eksekusi.
Sejarah terulang 130 tahun kemudian. Yuwen Yong, Kaisar Wu dari Zhou Utara mengeluarkan perintah pada tahun 574 untuk melarang agama Buddha dan Taoisme. Dengan menghancurkan kitab suci dan patung, ia memaksa para biksu dan penganut Tao untuk kembali ke kehidupan biasa. Kaisar meninggal di tahun berikutnya pada usia 36 karena penyakit menular, dengan sekujur tubuh bernanah.
Li Yan, Kaisar Wuzong dari Tang, melancarkan penganiayaan gelombang ketiga pada tahun 574. Dia hanya mengizinkan empat kuil di Chang'an, dua kuil di Luoyang, dan satu kuil di masing-masing 34 provinsi. Selain itu sudah tidak ada kuil yang diizinkan di tempat lain. Akibatnya, lebih dari 4.600 candi besar dihancurkan dan lebih dari 40.000 candi yang lebih kecil dihancurkan. Selain itu, kitab suci dibakar, patung Buddha dilebur untuk menghasilkan uang, dan lebih dari 260.000 biksu diubah menjadi manusia biasa. Kaisar ini juga menemui takdirnya. Karena penyakit aneh, kepalanya membengkak seperti sapi. Dengan borok di sekujur tubuh, matanya keluar, dan mulutnya berdarah, dia sangat kesakitan, berteriak siang dan malam. Pada akhirnya, dia meninggal pada usia 32 tahun.
Chai Rong, Kaisar Shizhong dari Zhou Akhir, juga melarang agama Buddha. Hanya satu kuil yang bisa dipertahankan di setiap daerah dan sisanya disingkirkan. Hanya mereka yang bisa melafalkan kitab suci Buddha dan memenuhi persyaratan lain yang diizinkan menjadi biksu; jika tidak, mereka akan dihukum. Lebih dari 30.000 kuil dan patung Buddha dihancurkan. Hampir satu juta biarawan dan biarawati berubah menjadi manusia biasa. Satu patung Bodhisattva di Kota Zhenzhou, Provinsi Henan yang sangat dihormati. Mereka yang dikirim untuk merusak patung itu berakhir dengan tangan patah dan meninggal. Chai Rong pergi ke sana sendiri untuk menghancurkan patung itu dengan menggunakan kapak besar memukul dada patung.
Empat tahun kemudian, Chai Rong tiba-tiba sakit dengan borok di dadanya. Tidak lama setelah itu, boroknya memburuk dan dia meninggal mengenaskan pada usia 39 tahun.
Dalam empat gelombang penganiayaan yang dijelaskan di atas, yang terlama adalah kurang dari enam tahun dan yang terpendek hanya delapan bulan. Setiap kali setelah penganiayaan, para penerusnya selalu menghidupkan kembali agama Buddha, mengembalikan tradisi dan melanjutkan peradaban.
Penganiayaan di Kekaisaran Romawi
Dalam tiga ratus tahun pertama setelah agama Kristen diperkenalkan, juga mengalami penganiayaan secara brutal. Nero, Kaisar Romawi kelima, menyalakan api selama seminggu pada tahun 64 M, yang menghancurkan dua pertiga wilayah Roma. Menyalahkan orang Kristen atas pembakaran itu, ia memulai gelombang penganiayaan pertama kekaisaran.
Sejarawan Tacitus dalam Annals menulis, “Pertama, kemudian anggota sekte yang mengaku ditangkap; selanjutnya, berdasarkan pengakuan mereka, sejumlah besar anggota dihukum, bukan karena pembakaran tetapi karena kebencian terhadap umat manusia.” "Dan cemohan menyertai akhir mereka: mereka ditutupi dengan kulit binatang buas dan dicabik sampai mati oleh anjing; atau mereka diikat di salib, dan, ketika siang hari berlalu dibakar untuk dijadikan lampu di malam hari.”
Tacitus melanjutkan, "Nero telah menawarkan Tamannya untuk tontonan, dan memberikan pameran di Circus-nya, bercampur dengan kerumunan dalam kebiasaan seorang kusir, atau dipasang di keretanya."
Orang-orang Kristen juga dianiaya pada masa pemerintahan Marcus Aurelius, yang merupakan kaisar Romawi antara tahun 161 dan 180, dan seorang filsuf Stoa. John Foxe dalam Book of Martyrs menulis, “Kekejaman yang digunakan dalam penganiayaan ini sedemikian rupa sehingga banyak penonton bergidik ngeri saat melihatnya, dan tercengang melihat keberanian para penderitanya.” “Beberapa dari para martir diharuskan untuk melewati, dengan kaki mereka yang sudah terluka, di atas duri, paku, cangkang tajam, dll. pada titik mereka, yang lain dicambuk sampai urat dan pembuluh darah mereka terbuka, dan setelah menderita siksaan yang paling menyiksa yang bisa dilakukan, mereka dihancurkan dengan kematian yang paling mengerikan.” Germanicus, misalnya, diumpankan ke binatang buas karena keyakinannya pada agama Kristen.
Penganiayaan Diocletianic yang dimulai pada tahun 303 adalah penganiayaan terakhir dan paling parah terhadap orang-orang Kristen di Kekaisaran Romawi. Serangkaian dekrit dikeluarkan untuk mencabut hak-hak hukum orang Kristen dan memerintahkan mereka untuk mematuhi praktik keagamaan lainnya.
Dalam Book of Martyrs, Foxe mencatat sepuluh penganiayaan selama Kekaisaran Romawi. Namun, bukannya tersingkirkan, praktik tersebut malah menarik semakin banyak orang. Jumlah orang Kristen sekitar 7.500 pada tahun 100 M, yang tumbuh menjadi sekitar 200.000 pada akhir abad kedua, dengan 7.000 orang Kristen hanya di Roma saja. Jumlahnya semakin meningkat menjadi sekitar satu juta pada tahun 250 M, dan lebih dari enam juta pada tahun 300 M, dengan lebih dari 1.800 gereja.
Pada tahun 313, Konstantinus Agung dan rekan-kaisarnya Licinius mengeluarkan Dekrit Milan. Ini memberikan status hukum Kristen dan menghentikan penganiayaan.
Kebebasan Berkeyakinan
Lebih dari 1.000 tahun telah berlalu sejak gelombang terakhir penindasan terhadap agama Buddha dan Kristen yang disebutkan di atas. Meskipun brutal pada saat itu, peristiwa penganiayaan bagaikan riak di sungai panjang sejarah. Meskipun demikian, mereka memberikan pelajaran bagi masyarakat modern kita, dan memberikan contoh bagaimana orang tetap teguh terhadap keyakinan yang lurus ketika menghadapi tantangan.
Deklarasi Kemerdekaan yang disahkan oleh Kongres AS pada tahun 1776 mengatakan, “Kami menganggap kebenaran ini dengan sendirinya sebagai bukti, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka diberkahi oleh Sang Pencipta mereka dengan Hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, bahwa di antaranya adalah Kehidupan, Kebebasan dan pencarian Kebahagiaan.” Ini menunjukkan bagaimana kebebasan berkeyakinan adalah fondasi dunia modern kita.
Tetapi hal-hal berubah secara drastis setelah komunisme muncul. Karl Marx menulis, “Agama adalah candu masyarakat. Ini adalah keluhan makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tak berperasaan, dan jiwa dari kondisi tak berjiwa kita.” Vladimir Lenin percaya hal yang sama. “Agama adalah candu massa.”
Setelah menyebabkan teror, darah, dan kelaparan, komunisme diperkenalkan ke Tiongkok, di mana mesin kebrutalan, pembunuhan, dan kebohongan ditingkatkan dan dioperasikan dengan cara yang lebih canggih.
Konstitusi Tiongkok menetapkan “Warga Republik Rakyat Tiongkok menikmati kebebasan berbicara, pers, berkumpul, berserikat, prosesi, dan demonstrasi.” (Pasal 35) dan “Warga Republik Rakyat Tiongkok menikmati kebebasan beragama.” (Pasal 36) Namun pada kenyataannya hak-hak masyarakat tidak dilindungi. Partai Komunis Tiongkok menindas tuan tanah dan kapitalis pada 1950-an, dan menghapus tradisi dalam Revolusi Kebudayaan pada 1960-an. Demikian pula, Konstitusi tidak melindungi mahasiswa dan pendukung demokrasi dalam Pembantaian Lapangan Tiananmen 1989, atau praktisi Falun Gong ketika mereka mulai menghadapi penganiayaan pada 1999.
(Bersambung)
Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta © 1999-2025 Minghui.org