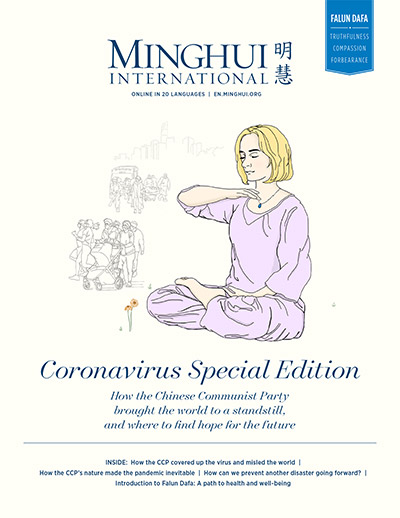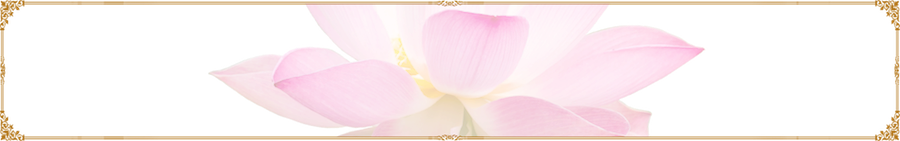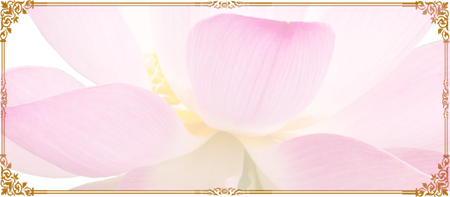(Minghui.org) Salam Guru. Salam, rekan-rekan praktisi.
Selama 17 tahun berkultivasi, saya menulis banyak artikel berbagi pengalaman, yang sebagian besar berfokus pada menggunakan keterampilan saya untuk membantu Guru dalam pelurusan Fa. Hari ini, saya ingin berbagi pengalaman kultivasi saya melalui interaksi dengan orang-orang di sekitar saya.
Saya tidak pernah dekat dengan ibu. Dia selalu bersikap negatif dan sering mengeluh, jarang memuji atau menyemangati saya.
Tak lama setelah saya mulai berlatih Falun Dafa, ibu saya didiagnosis menderita kanker usus besar stadium lanjut. Ia kemudian pulih secara ajaib dengan melafalkan dua kalimat, "Falun Dafa baik, Zhen-Shan-Ren (Sejati-Baik-Sabar baik)." Saat mengunjungi saya di AS, dan dengan dorongan dari ayah, ia memutuskan untuk berlatih Falun Dafa.
Namun, pemahamannya tentang Fa tetap pada tingkat persepsi. Ia menanggapi pertanyaan tentang apakah harus minum obat secara dangkal. Setiap kali muncul penderitaan, ia bereaksi seolah langit akan runtuh, berulang kali meminta nasihat saya. Saya sering terdiam ketika ia berkata, "Kamu tidak tahu apa yang ibu rasakan karena kamu belum mengalaminya sendiri."
Saya meyakinkan orang tua pindah dari Tiongkok ke rumah yang hanya berjarak lima menit dari tempat saya. Tak lama setelah mereka menetap, ibu mulai mendesak saya untuk mengajukan perawatan kesehatan bagi mereka; membawa mereka ke berbagai dokter; dan bahkan membujuk ayah mencabut semua giginya yang tersisa. Setelah itu, ayah berhenti menelepon untuk mengklarifikasi fakta, menjelaskan bahwa berbicara tanpa gigi membuatnya sulit untuk dipahami, apalagi untuk mengklarifikasi fakta kepada orang-orang di Tiongkok. Akibatnya, di tengah perasaan bergejolak terhadap ibu, rasa kesal pun tumbuh. Saya kesal karena pemahamannya yang terbatas justru menarik ayah saya lebih dalam ke dalam masyarakat manusia biasa.
Untuk waktu yang lama, setiap kali saya mengunjungi mereka, saya hanya berbicara dengan ayah dan menghindari ibu. Didiagnosis menderita penyakit Parkinson, dia duduk di sofa, tidak mampu menoleh atau berjalan menghampiri kami. Dia merasa sedih dan tak berdaya, tetapi saya tidak merasa bersalah—saya yakin saya sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan baik. Apa lagi yang bisa dilakukan? Dengan kepribadian kami yang sangat berbeda, kami bagaikan minyak dan air, tak mampu menyatu.
Suatu hari, seorang praktisi datang bersama saya mengunjungi orang tua saya. Saat kami berdiskusi tentang kultivasi, ibu saya mengatakan sesuatu yang menyentuh hati, dan saya pun tak kuasa menahan diri untuk menanggapinya dengan nada merendahkan. Sebelum saya sempat menyelesaikannya, praktisi itu dengan tegas menyela saya. Dalam perjalanan pulang, ia dengan tegas mengkritik perilaku saya, mengatakan bahwa saya tidak menunjukkan belas kasih seorang kultivator maupun bakti yang diharapkan dari orang biasa. Saya tercengang.
Mencari ke dalam, saya menyadari prasangka saya terhadap ibu. Ya, pencerahannya mungkin terbatas—tapi kenapa? Dia tidak pernah menentang Fa. Keterbatasan pencerahan itu relatif. Dibandingkan dengan praktisi yang tekun, bukankah saya juga memiliki keterbatasan? Guru mengajarkan Fa kepada orang-orang biasa, ada yang pencerahannya lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Namun, Guru menunjukkan belas kasih yang sama kepada semua orang, terlepas dari tingkatan mereka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Siapakah saya yang begitu arogan?
Berbicara merendahkan ibu—bukankah itu menunjukkan kurangnya belas kasih? Kehidupannya di Tiongkok jauh lebih bervariasi daripada kehidupan monoton di sini. Jadi, mengapa dia setuju untuk pindah? Bukankah karena dia memercayai saya dan menaruh harapan tinggi? Bagaimana mungkin saya memperlakukannya seperti itu?!
Saya mulai lebih sering mengunjungi Ibu. Ketika Ayah sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, saya mengurus kebutuhan sehari-harinya. Suatu kali, Ibu kaku di tengah lorong saat berjalan. Saya memeluknya dari belakang, membimbingnya maju sedikit demi sedikit, seperti balita yang sedang belajar berjalan. Ketika kami akhirnya sampai di kamar tidur, saya mengangkatnya ke tempat tidur untuk beristirahat. Ibu menatap saya dengan tatapan lembut.
Suatu hari, tepat ketika saya hendak meninggalkan rumah mereka, ibu tiba-tiba berkata dalam bahasa Inggris, "Saya mencintaimu." Saya begitu terkejut hingga saya tertegun, tak mampu menjawab. Ia belum pernah mengatakan hal seperti itu kepada saya sebelumnya. Bahkan puluhan tahun yang lalu, di bandara ketika saya akan berangkat ke AS untuk melanjutkan pendidikan, yang ia katakan hanyalah agar saya bergegas sehingga tidak ketinggalan pesawat. Kali ini, dengan air mata berlinang, saya memeluknya, mencium keningnya, dan mengatakan bahwa saya juga mencintainya. Sejak saat itu, tak ada lagi sekat yang tersisa di antara kami.
Kemudian, ayah juga membutuhkan perawatan, dan saya menyewa pengasuh yang tinggal di rumah untuk mereka. Ayah bisa bergaul dengan siapa saja, sedangkan ibu sebaliknya. Hal ini sangat menyakitkan baginya, dan ia hanya bisa mencurahkan isi hatinya kepada saya. Saya berusaha sebaik mungkin untuk menghiburnya, membangkitkan semangatnya, dan memediasi hubungan yang tegang antara ibu dan pengasuhnya.
Para pengasuh datang dan pergi—semua karena ibu. Setiap kali, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada ayah sambil menangis, dan setiap kali pula saya harus menanggung tekanan ketidakpastian, memaksa diri untuk mencari pengasuh berikutnya yang lebih tangguh. Saya merasa lelah—baik secara fisik maupun mental. Tapi saya tak lagi kesal, karena saya telah memahami kepedihan ibu.
Terkadang, saya sendiri harus ikut membantu sebagai pengasuh. Suatu kali, saat saya membersihkannya setelah buang air besar, tanpa disadari ia mengeluarkan tinja ke tangan saya. Saya pun mencuci tangan dengan tenang, seperti yang biasa saya lakukan saat mengganti popok bayi saya sendiri.
Beberapa bulan yang lalu, ibu saya koma di rumah. Selama lima hari ia tertidur lelap, saya sering memutarkan musik Dafa Pudu di sisinya. Akhirnya, dia meninggal dunia dengan tenang, dengan senyum tipis di wajahnya.
Saya menulis, dalam bahasa Mandarin dan Inggris, tentang prinsip Zhen-Shan-Ren (Sejati, Baik, Sabar) memurnikan hati saya yang dingin dan egois, memberi saya kesempatan untuk meningkatkan diri dan mendampingi ibu—tanpa penyesalan—menjalani tahap akhir hidupnya. Saya membagikan kisah ini kepada tim perawat ibu saya, tetangga, kerabat di Tiongkok, dan teman-teman di sekitar saya, dan kisah ini menjadi cara yang sangat efektif untuk mengklarifikasi fakta.
Setelah ibu meninggal, kesehatan fisik dan mental ayah perlahan menurun. Saya mengunjunginya hampir setiap hari, untuk menyemangatinya, mengenang masa lalu, dan berbagi kabar terbaru dari pekerjaan dan kehidupan saya. Tidak mudah untuk menjaga hubungan ini setiap hari.
Putri saya kembali dari Pantai Timur selama seminggu dan menyarankan agar seluruh keluarga menghabiskan waktu bersama di rumah liburan di Oregon. Saya sangat menantikan minggu berharga itu bersamanya dan bekerja jarak jauh.
Sehari sebelum keberangkatan, saya pergi mengunjungi ayah. Yang mengejutkan saya, kondisinya memburuk sedemikian rupa sehingga saya tidak yakin apakah saya bisa bertemu dengannya lagi saat saya kembali. Dengan ragu, saya bertanya, "Ayah, bagaimana kalau saya tidak pergi?" Berbeda dengan penolakannya yang sopan, ia hanya menjawab, "Oke." Hati saya terpuruk—saya tahu sudah tiba saatnya saya menghadapi keputusan yang sulit.
Selama masa COVID, seperti banyak remaja lainnya, putri saya mulai berjuang melawan masalah kesehatan mental. Suatu hari, ia dengan sungguh-sungguh mengatakan ingin menyayat pergelangan tangannya dengan silet. Karena tidak melihat tanda-tanda cedera, saya pikir ia hanya mencari perhatian. Lagi pula, kami baru saja kembali dari perjalanan khusus yang telah saya rencanakan dengan matang untuk menghiburnya. Saya pun berpikir, "Saya sudah berbuat begitu banyak untukmu; apakah kamu hanya memanfaatkan kelebihanmu?" Jadi, saya menepisnya dengan beberapa kata. Saya tidak menyadari bahwa tanggapan saya sangat menyakitinya. Sejak saat itu, ia mulai menjauh, menjadi acuh tak acuh, dan bahkan ingin segera berangkat kuliah.
Perubahannya membuat saya kecewa sekaligus bingung. Saat itu, saya pikir itu hanya masalah gejolak masa pertumbuhan—terutama bagi anak-anak yang dibesarkan di AS, di mana pemberontakan remaja adalah hal yang umum. Selama semester terakhir SMA-nya, putri saya mengalami anoreksia. Suami saya tidak mengerti dan mengira dia mencari-cari alasan untuk menghindari lomba lari, karena dia anggota tim lari sekolah. Merasa tak berdaya, dia meminta dukungan saya. Pemahaman dan dorongan saya akhirnya menyadarkannya. Beberapa minggu sebelum berangkat kuliah, dia mengungkapkan alasan sebenarnya di balik hubungannya yang renggang dengan saya. Saya tercengang. Saya dengan tulus meminta maaf. Dia agak terkejut bahwa ibunya yang biasanya keras kepala dan kaku menjadi rendah hati dan meminta maaf.
Dia berangkat kuliah ribuan kilometer dari rumah, tetapi awalnya sulit. Hanya dalam beberapa bulan, dia mengalami depresi. Di saat-saat tergelap dan terpuruknya, saya ada di ujung telepon, menawarkan dukungan. Setelah berganti tiga penerbangan dari Eropa, akhirnya saya sampai di kampusnya. Dia berlari menghampiri saya dan memeluk saya, pelukan terlama yang pernah saya rasakan—berlangsung selama 60 detik penuh. Sejak saat itu, kami menjadi sahabat baik.
Kini, sebagai seorang kultivator, saya harus memilih antara keluarga dan tugas. Sekembalinya ke rumah, saya mengabari keluarga tentang kondisi ayah. Suami saya terus bertanya apakah saya yakin dengan keputusan saya—mengingatkan saya bahwa saya selalu bisa terbang pulang sendirian jika terjadi keadaan darurat.
Yang menenangkan saya adalah dukungan dari anak saya. Keesokan harinya, sebelum ia pergi, putri saya memeluk saya erat-erat dan mengingatkan saya untuk menjaga diri sendiri. Pengertian dan perhatiannya meredakan rasa sakit yang masih membekas di hati saya.
Keluarga Suami Saya
Sekarang, izinkan saya bercerita tentang dua perempuan dari pihak suami saya. Ibu mertua saya, Kathy, adalah sosok yang penyayang namun juga berkemauan keras. Keluarganya menjulukinya "Sang Ratu".
Beberapa minggu setelah saya mendapatkan Fa, saya membeli tiket Shen Yun untuk seluruh keluarga. Mertua saya yang pertama kali menonton. Meskipun mereka merasa pertunjukan itu indah, mereka tidak sepenuhnya memahami pesannya yang mendalam. Reaksi mereka memengaruhi suami saya, yang kemudian memutuskan untuk tidak menontonnya. Kejadian itu menanamkan benih kebencian terhadap Kathy di hati saya.
Kemudian, dia juga didiagnosis menderita Parkinson, seperti ibu saya. Untuk menunjukkan belas kasih, saya memperkenalkan Falun Dafa kepadanya. Namun, dia segera menolak. Penolakannya semakin memperdalam kebencian saya terhadapnya.
Seiring saya terus belajar Fa dan menyaksikan kondisi ibu mertua saya yang semakin memburuk, rasa belas kasih saya mulai muncul. Sikap saya pun berubah—dari kepedulian yang awalnya dangkal menjadi pengertian yang tulus, dan akhirnya menjadi sukarelawan untuk ikut menanggung beban tugas-tugas keluarganya.
Kathy sangat menghargai kumpul keluarga dan senang mengadakan pesta liburan untuk keluarga, kerabat, termasuk sepupu, teman, dan tetangga. Namun, karena kesehatannya menurun, ia tidak lagi mampu melakukannya. Karena kasihan, saya menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah. Hal itu bertentangan dengan kebiasaan saya—biasanya, kami sering merencanakan perjalanan selama liburan agar bisa menghindari undangan. Namun kali ini, saya memilih untuk tidak melakukannya dengan cara lama.
Thanksgiving terakhir, saya menyiapkan pesta kalkun tradisional, dan semua orang senang. Tiba-tiba, Kathy menatap saya dan berkata, "Terima kasih." Setelah jeda sejenak, ia menambahkan, "Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk saya."
Di ulang tahun pernikahan mertua saya yang ke-60, saya naik ke panggung untuk berbagi cerita: ketika putri saya baru berusia beberapa bulan, Kathy akan berkendara tiga jam sekali jalan untuk menghabiskan sehari bersama cucunya—tanpa keluhan, tanpa tuntutan, hanya cinta sejati. Saya menatap Kathy dan berkata dengan tulus, "Bu, jika saya cukup beruntung menjadi seorang nenek, saya berharap bisa menjadi anggun, menyenangkan, dan sayang seperti Ibu." Ruangan itu bergemuruh dengan tepuk tangan, dan air mata menggenang di mata Kathy.
Ipar saya, Kelly, memang ramah dan punya banyak teman, tapi dia cenderung melebih-lebihkan sesuatu. Sepanjang SMP dan SMA, dia hidup di bawah bayang-bayang prestasi kakak laki-lakinya. Suami saya membiayai kuliahnya sendiri tanpa meminta sepeser pun dari orang tuanya. Sebaliknya, Kelly terus menerima bantuan keuangan dari orang tuanya—bahkan hingga hari ini.
Suatu hari saat Natal, Kelly menelepon ibunya, mengaku tidak bisa pulang karena sedang bepergian ke Afrika. Ketika telepon diserahkan kepada kami, ia bercanda, "Di sini, di San Francisco, cuacanya cerah dan menyenangkan." Kami merasa upayanya untuk melibatkan kami dalam tipuannya itu kasar sekaligus mengerikan. Akhirnya, kami tak tahan lagi dan mengatakan yang sebenarnya kepada Kathy. Setelah itu, Kelly memutuskan pertemanan dengan saya di Facebook.
Saya marah sekali. Sayalah yang berhak memutuskan hubungan dengan orang seperti dia, tapi dia malah mengambil langkah pertama. Konyol sekali!
Tapi saya adalah seorang kultivator. Setelah saya tenang, saya menyadari bahwa meskipun di permukaan, perasaan saya terhadap Kelly tampak dibentuk oleh pengaruh suami saya, di balik semua itu, saya menyimpan sifat iri hati yang sangat tersembunyi.
Sejak menikah dengan suami saya, Kathy bersikeras agar seluruh keluarga menempuh perjalanan ratusan kilometer ke rumah liburannya untuk merayakan Natal putih setiap tahun. Ia juga menyarankan agar, demi menghormati budaya saya, saya menyiapkan makan malam khas Tiongkok pada Malam Natal. Namun, ada masalah—putrinya, Kelly, empat tahun lebih tua dari saya. Mengapa saya yang harus mengumpulkan semua bahan, berkendara sembilan jam ke rumahnya, dan, setelah seharian bermain ski, menghabiskan waktu berjam-jam memasak sementara yang lain beristirahat? Kelly tidak perlu melakukan apa pun.
Terlebih lagi, kami menyaksikan Kathy memberi Kelly cek dalam jumlah besar, beserta uang tambahan untuk membiayai perjalanan internasional tahunannya. Setiap kali Kelly makan malam bersama kami, selalu kami yang membayar tagihannya.
Tapi kenapa saya iri padanya? Memang benar ada banyak hal tentangnya yang tak saya suka. Namun, dinamika sebab-akibat dalam keluarganya bukanlah sesuatu yang sepenuhnya saya pahami. Bukankah kehadirannya dimaksudkan untuk membantu saya meningkatkan Xinxing dan menaikkan tingkat melalui konflik? Apa gunanya mendesak suami saya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya? Itu hanya akan menyakiti Kathy. Sebagai seorang kultivator, bukankah kita menekankan kesabaran? Jadi, di mana kesabaran saya?
Saya menyingkirkan prasangka buruk dan mencoba melihat sisi positif Kelly. Suatu kali, dia mampir ke rumah kami setelah mengunjungi teman-temannya, berharap bisa mengobrol dengan suami saya. Tapi suami saya sedang tidak di rumah, jadi saya menyapanya dengan hangat. Selama percakapan kami, dia menjadi emosional saat membahas beberapa masalah yang berhubungan dengan kakaknya. Saya mendengarkan dengan tenang, tanpa menghakimi atau membiarkan emosinya memengaruhi saya. Saya mencoba menempatkan diri di posisinya dan benar-benar memahami perspektifnya. Akhirnya, saya berkata, "Percayalah, kakakmu tidak akan pernah mencoba memanipulasimu." Dia tertegun sejenak, lalu menangis tersedu-sedu.
Kemudian, Kelly berkata kepada saya, "Kita harus sungguh-sungguh bertukar pikiran. Kalau kamu di kota, mampirlah." Dulu, saya mungkin berpikir dia hanya bersikap sopan di depan Kathy. Tapi sekarang, saya tidak lagi menganggapnya seperti itu. Saya menerima ajakannya dengan anggukan. Kemudian, saya meluangkan waktu untuk makan malam bersamanya dan pacarnya. Mereka tersentuh oleh ketulusan dan keterbukaan saya. Setelah saya menceritakan perkenalan saya tentang Shen Yun, pacarnya dengan tulus berjanji mereka akan menontonnya.
Penutup
Saya harus berkendara di jalan pegunungan yang berkelok-kelok untuk pulang pergi dari rumah ke kantor. Terkadang, di setiap tikungan tajam, saya tiba-tiba merasa gugup—telapak tangan berkeringat, mata menatap ke depan, takut satu langkah yang salah akan membuat saya menabrak pagar pembatas jalan atau jatuh ke jurang. Semakin cemas di hati, semakin terasa seperti setir mobil bekerja melawan saya. Namun, ketika saya tidak berpikir berlebihan dan mengikuti alur jalan, mobil secara alami akan meluncur melewati tikungan—dan hati saya pun tenang.
Bukankah kultivasi kita sama? Sesulit apa pun jalannya, jika pikiran kita jernih dan fokus—hanya diisi dengan Fa—kita akan tetap tenang dan tenteram. Karena jalan yang telah Guru tetapkan bagi kita, betapa pun beratnya, itulah yang terbaik.
Di atas adalah pengalaman saya. Mohon beri tahu jika ada yang kurang tepat. Terima kasih, Guru. Terima kasih semuanya.
(Artikel pilihan yang dibacakan pada Konferensi Fa San Francisco 2025)
Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta © 1999-2025 Minghui.org